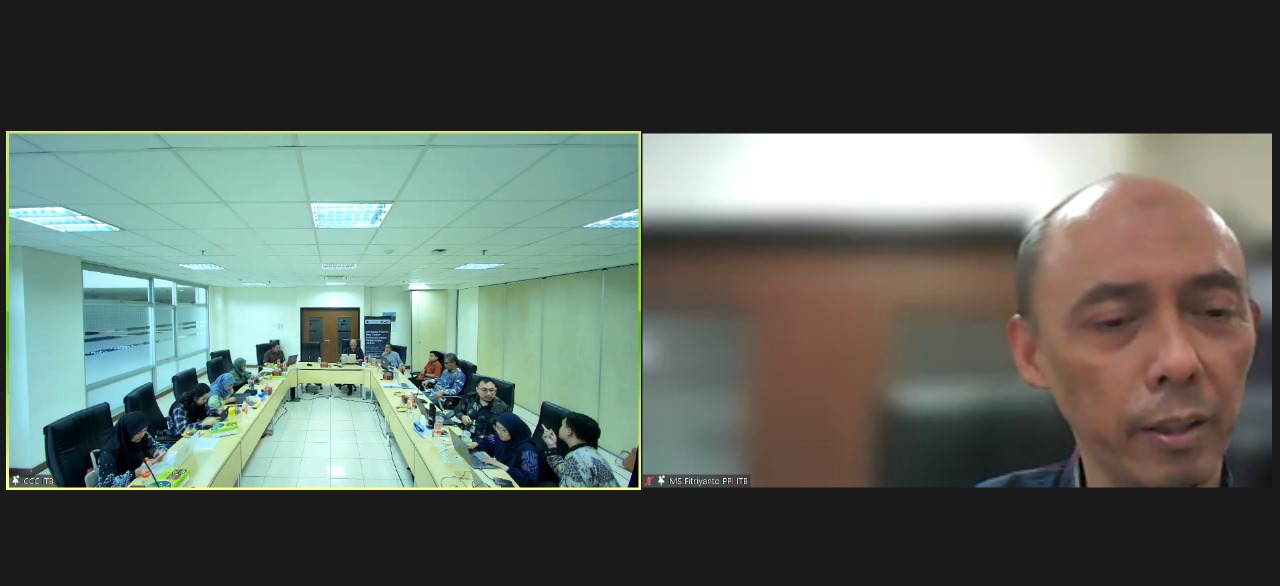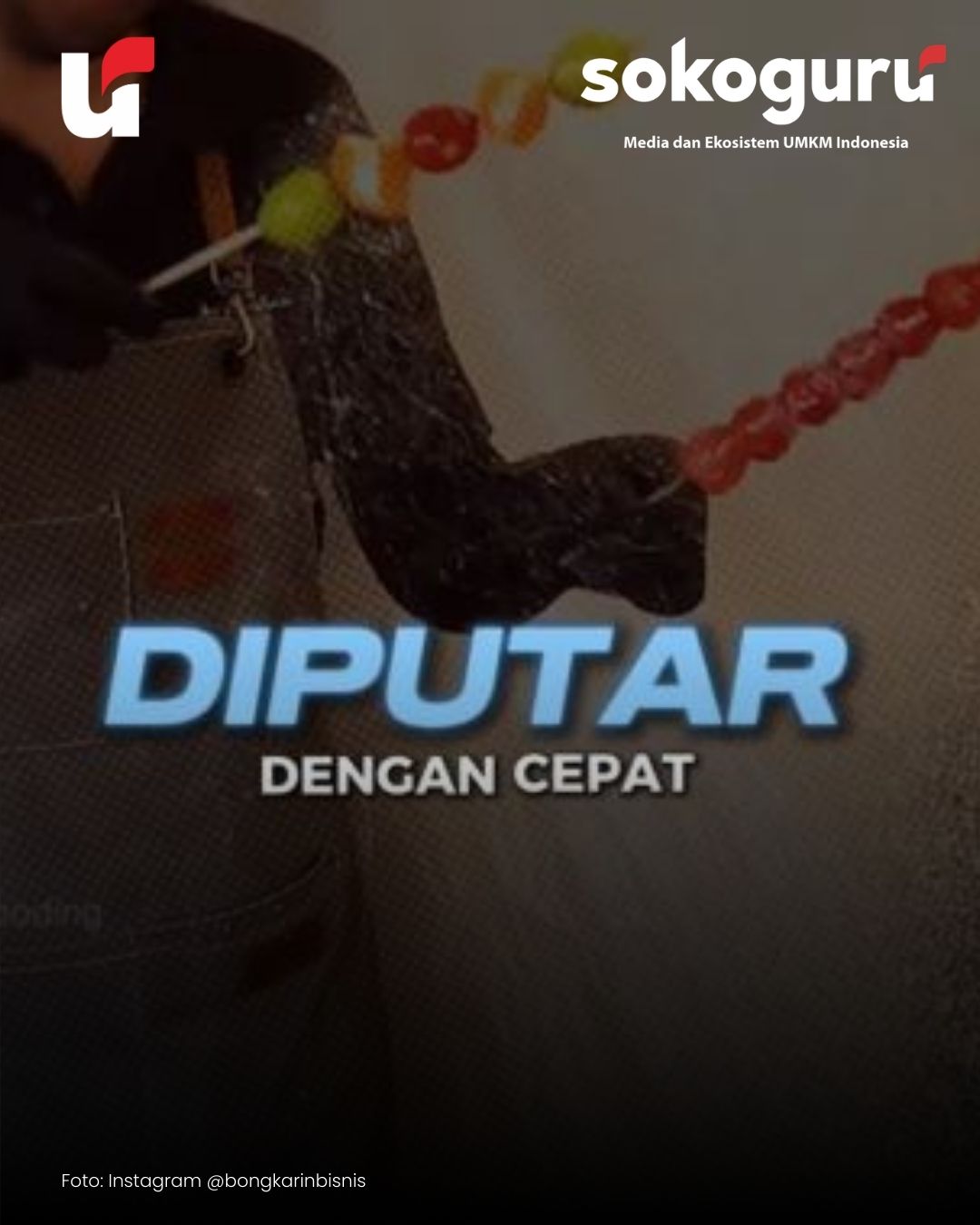UPAYA rehabilitasi mangrove di berbagai wilayah Indonesia terus menghadapi tantangan yang kompleks meskipun pentingnya ekosistem itu dalam mitigasi perubahan iklim semakin diakui.
Salah satu contoh nyata adalah rehabilitasi mangrove di Muara Bojong Salawe, yang dilakukan setelah tsunami Pangandaran pada 2006. Program itu menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mangrove, meskipun luas areal rehabilitasi relatif kecil.
“Mangrove memiliki potensi besar dalam menyimpan karbon, tetapi proses rehabilitasi sering kali terganggu oleh kesulitan dalam menemukan lahan yang cocok untuk penanaman bibitnya serta mampu mengajak masyarakat untuk ikut serta merehabilitasi lahan mangrove yang rusak,” kata Dosen Kelompok Keahlian Ekologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (ITB), Elham Sumarga pada Workshop Potensi Blue Carbon Indonesia dalam Perdagangan Karbon,Selasa (25/6).
Baca juga: ITB Bentuk Satgas Aplikasi AI sebagai Komitmen dalam Transformasi Tridarma
Acara yang dihelat oleh Pusat Perubahan Iklim ITB tersebut berlangsung secara daring dari Gedung Riset dan Inovasi Lt. 3, Jln. Ganesha No. 10, Kota Bandung.
"Langkah pertama biasanya pembibitan, dan ketika bibit siap, sulit menemukan lahan yang sesuai. Akibatnya, banyak lahan penanaman yang tidak berhasil dan gagal total,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Muhammad Ilman, menyampaikan, data menunjukkan 93% mangrove di Indonesia berada dalam kondisi baik, namun terdapat sekitar 756.000 hektare (ha) yang rusak dan membutuhkan restorasi.
Baca juga: Tanam 500 Mangrove di Hari Lingkungan Hidup, Pertagas Hijaukan Pesisir Indramayu
Sebagian besar dari lahan rusak itu, lanjutnya, adalah tambak tradisional, yang sering kali sulit untuk dikonversi kembali menjadi hutan mangrove karena kepentingan ekonomi masyarakat setempat dalam budi daya udang.
"Permintaan udang sangat besar, meski harganya fluktuatif, ini menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat," jelas Ilman.
Menurutnya, tantangan utama dalam rehabilitasi adalah meyakinkan pemilik tambak untuk menanam mangrove, yang secara ekonomi kurang berpengaruh bila dibandingkan dengan tambak udang.
Baca juga: Tingkatkan Kunjungan Wisatawan, Ekowisata Mangrove Pangkal Babu, Jambi, Perlu Dibenahi
Meski demikian, kata Ilman lagi, rehabilitasi mangrove terus dilakukan, dengan kelompok tani seperti "Mangrove Berkah Anugerah" di Muara Bojong Salawe yang berperan aktif. Rehabilitasi di kawasan itu telah berhasil meningkatkan luasan mangrove dari 6 ha pada 2011 menjadi 24 ha pada 2021.
Peluang dan Tantangan
Konsep karbon biru, yang mengacu pada penyerapan karbon oleh ekosistem laut seperti mangrove, lamun, dan padang rumput laut, menjadi fokus dalam diskusi panel tersebut.
Para ahli membahas keunggulan dan kelemahan mangrove serta peluang perdagangan karbon biru di Indonesia. Ilman menekankan potensi besar Indonesia dalam mengelola ekosistem karbon biru.
"Dari penelitian kami, pengelolaan dan pelestarian ekosistem bisa mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 13 gigaton, berkontribusi 37% terhadap target pengurangan emisi global," ujarnya.
Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal pengelolaan lahan dan regulasi. "Perdagangan antarsektor masih belum diperbolehkan, dan perhitungan emisi karbon dari mangrove belum sepenuhnya memasukkan semua komponen gas rumah kaca seperti N2O," tambah Ilman.
Sementara itu, Rini Widyanti yang mewakili Direktur Pendayagunaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyoroti pentingnya integritas tinggi dalam perhitungan ekonomi karbon, tidak hanya berfokus pada karbon tetapi juga mempertimbangkan keanekaragaman hayati.
"Kita perlu menyusun metode perhitungan yang memasukkan semua aspek ini untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon biru," jelasnya lagi.
Rini menambahkan, pihaknya juga berkomitmen untuk menghitung dan menginventarisasi karbon biru di sektor lamun. Namun, mereka menghadapi kendala dalam pengumpulan data dan metode perhitungan yang belum seragam.
Restorasi Mangrove
Dalam workshop itu terungkap bahwa tantangan dalam restorasi mangrove sangat nyata di lapangan. Salah satu kendala terbesar adalah kesulitan dalam menemukan lahan yang cocok untuk penanaman bibit mangrove.
Sebabnya, kata Ilman lagi, banyak proyek rehabilitasi gagal karena bibit ditanam di lahan yang tidak sesuai, sehingga tidak dapat tumbuh dengan baik.
"Di Indonesia, sebagian besar proyek rehabilitasi mangrove tidak berhasil karena penanaman dilakukan di lahan yang tidak cocok," ungkapnya.
Masalah lain yang dihadapi adalah konflik kepentingan antara ekonomi lokal dan upaya konservasi. Budi daya udang, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak masyarakat pesisir, sering kali bertentangan dengan upaya konservasi mangrove.
"Permintaan udang sangat besar, meskipun harganya fluktuatif. Ini menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat. Upaya untuk mengganti tambak udang dengan hutan mangrove sering kali tidak diterima oleh masyarakat karena keuntungan ekonomi lebih rendah,” jelasnya lagi.
Namun, ada juga kisah sukses dalam upaya rehabilitasi mangrove. Di Muara Bojong Salawe, kelompok tani "Mangrove Berkah Anugerah" telah berhasil meningkatkan luas area mangrove secara signifikan.
Dari hanya 6 ha pada 2011, mereka berhasil memperluas area rehabilitasi menjadi 24 ha pada 2021. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, rehabilitasi mangrove dapat berhasil.
Peluang dan Tantangan
Perdagangan karbon biru di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, meskipun potensinya besar. Salah satu masalah utama adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perdagangan antarsektor.
Selain itu, perhitungan emisi karbon dari ekosistem mangrove belum mencakup semua komponen gas rumah kaca, seperti N2O, yang mengurangi nilai ekonomi karbon biru.
Untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon biru, diperlukan metode perhitungan lebih komprehensif yang mempertimbangkan tidak hanya karbon tetapi juga keanekaragaman hayati.
Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Pendayagunaan Masyarakat Pesisir KKP, telah berkomitmen untuk menghitung dan menginventarisasi karbon biru di sektor lamun. Namun, mereka menghadapi kendala dalam pengumpulan data dan metode perhitungan yang belum seragam.
"Kami butuh peran dari peneliti dan akademisi untuk membantu mengatasi tantangan ini," kata Rini Widyanti lagi.
Menurutnya, kolaborasi antara peneliti, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mengelola dan memanfaatkan potensi besar karbon biru di Indonesia. Dengan perubahan perilaku dan pendekatan yang lebih holistik, ekosistem karbon biru dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (Fajar Ramadan/SG-1)